
Baca cerita sebelumnya: Hitam Putih Sang Mahapatih (Bagian 2)
Menjelang tengah hari tampak sebuah kereta berkuda memasuki halaman rumah penginapan Sewu Klopo. Aku mengamati kedatangan mereka dari balik jendela kamarku. Dua orang pria berbadan tegap melompat dari atas kereta. Hup! Langkah mereka tegas. Suara kaki menapak tanah berdebu di musim kemarau.
Melihat postur tubuh mereka yang gagah dan tangkas bergerak, hal ini mengingatkanku pada para prajurit Kerajaan Jambangan Sari yang rajin berlatih perang. Aku berkhayal seandainya dua pemuda itu menjadi pengawalku di istana tentu aku akan merasa lebih aman saat melakukan tugas pengawasan daerah perbatasan.
“Waskita, apakah barangnya sudah disiapkan?” ujar salah satu pria yang kuketahui ternyata Widura.
Pertemuanku dengan Widura di tengah hutan tempo hari masih teringat jelas. Dia sedang bertengkar dengan istrinya dan keluar dari rumah dalam keadaan marah. Saat ini tidak tampak sedikit pun sisa amarah Widura. Sebaliknya, wajahnya terlihat berseri-seri sejak kereta kuda memasuki halaman penginapan. Kiranya penginapan ini menjadi tempat kesukaannya saat beristirahat.
Waskita terlihat menyambut dua pria itu dengan buru-buru.
“Semua sudah siap, Widura. Ayo pindahkan kereta kudamu ke belakang penginapan,” ujar Waskita.
Tak lama kemudian, Widura menuntun kudanya ke arah belakang penginapan dan diikuti kawannya.
Aku beranjak keluar dari kamar. Aku ingin menyapa Widura. Meskipun pertemuanku dengan Widura baru sekali, tapi aku merasa pria ini bisa memberikan banyak informasi padaku perihal para pemberontak Sewu Klopo.
Aku berjalan pelan ke arah pintu belakang rumah penginapan. Kuputuskan tidak langsung menyapa Widura. Aku berdiri tegak sambil memasang pendengaran pada percakapan mereka dari balik dinding bambu. Ku ambil jarak aman supaya bisa mendengar percakapan mereka tanpa terlihat oleh tiga orang pria itu.
Waskita, Widura dan pria kawan Widura bahu membahu memindahkan karung beras dan ketela dari gudang ke dalam kereta. Satu, dua, dan tiga. Ada tiga karung beras berukuran sedang telah berpindah. Hal ini diikuti oleh dua karung ketela. Bahan-bahan makanan itu kira-kira cukup untuk dimakan sepuluh orang dalam waktu sepekan.
Peluh bercucuran di tubuh Widura yang bertelanjang dada. Kulitnya tampak mengkilat terpapar sinar matahari. Dari tempat pengamatanku sini, Widura tampak perkasa kendati nafasnya terdengar memburu. Pantas saja isteri Widura tidak ingin berpisah dengannya walau Widura sudah terang-terangan tidak mau kembali ke rumah. Mana ada wanita yang rela melepaskan suami berotot perkasa seperti Widura.
“Kita istirahat dulu sebentar,” ujar Widura pada dua orang pria yang membantunya memindahkan karung. Ketiganya berjalan ke arah gubuk tempatku berbicara dengan simbok penjaga taman tadi pagi. Angin semilir memberikan pasokan udara yang cukup bagi pernapasan mereka.
Aku masih mengawasi mereka dari kejauhan. Jarakku dengan mereka bertiga sekitar sepuluh langkah. Kurasa cukup mudah bagiku untuk mencuri dengar pembicaraan mereka. Ku toleh ke kiri dan kanan. Kulihat aman. Tidak ada orang berlalu lalang disini.
Terlihat Waskita menuang air kelapa muda ke dalam tiga batok kelapa. Setiap orang mendapat bagian satu batok. Mereka minum air kelapa dan langsung habis seketika.
“Bagaimana perjalananmu hari ini, Widura?” tanya Waskita.
“Cukup mudah. Untung sebulan ini tidak turun hujan sehingga jalan desa tidak sulit dilalui,” jawab Widura.
“Lalu, bagaimana perkembangan penginapan ini, Waskita?” Widura bertanya balik kepada lawan bicaranya.
“Penginapan selalu penuh tamu. Sama seperti bulan kemarin, kebanyakan tamu adalah orang dari jauh,” kata Waskita.
“Apakah ada tamu yang bertingkah mencurigakan?” tanya Widura sambil memandang Waskita dengan muka serius.
Deg! Aku merasa sedang dicurigai oleh Widura dan Waskita. Apakah aku harus segera kabur dari penginapan ini? Ataukah aku harus melanjutkan penyamaran ini hingga beberapa hari ke depan? Ku lihat Waskita memandang balik wajah Widura dengan tenang.
“Tidak ada tamu mencurigakan. Hanya tamu-tamu biasa yang enggan membuka kamar sampai siang hari,” jawab Waskita.
“Jangan bilang kalau tamu-tamu yang menginap disini adalah para pasangan pengantin yang sedang berbulan madu,” kata Widura diiringi senyum.
Ketiga pria itu lantas tertawa bersama. “Kalau sampai itu terjadi, bisa dipastikan kamu mati berdiri karena menjadi obat nyamuk untuk acara bercinta mereka,” imbuh Widura sambil menunjuk muka Waskita.
Sekali lagi, Waskita tertawa terbahak-bahak sambil mengumpat Widura.
“Memangnya kamu. Mau datang kesini hanya untuk bersenang-senang dengan juraganku saja,” kata Waskita.
“Ah, kamu bisa saja,” ujar Widura.
Kupandang sekeliling penginapan sepi. Hanya suara tawa mereka bertiga yang memecah keheningan suasana desa Sewu Klopo. Saat hati telah senang, mudah bagi kita untuk masuk ke pembicaraan orang lain. Inilah waktunya bagiku untuk memunculkan diri di hadapan Widura.
Aku berjalan pelan ke arah mereka bertiga. Widura menatap ke arahku. Matanya menyipit sejenak. Lalu sorot matanya berbinar menyadari aku yang muncul di hadapannya secara tiba-tiba.
“Respati! Ini benar kamu, Respati?” ucap Widura seolah tak percaya.
“Apa kabar Widura? Rupanya kita bertemu lagi disini,” jawabku berpura-pura baru saja tiba di tempat ini padahal aku sudah mendengar pembicaraan mereka sejak awal.
“Aku baik-baik saja, Respati” kata Widura.
Menyadari ada tamu penginapan yang akan berbicara dengan Widura, Waskita dan teman Widura beranjak dari tempat duduknya. Mereka berdua berpamitan menuju ruang dapur untuk makan siang. Kini hanya tinggal Widura berdua denganku saja.
“Maaf, kalau boleh tahu bagaimana kabar isterimu di rumah?” tanyaku pada Widura.
“Dia sehat dan tak kurang apapun,” jawab Widura singkat.
“Apakah isterimu aman di rumah sementara saat ini sedang berkembang berita pemberontak Sewu Klopo sedang berkeliaran?” kataku memancing informasi dari mulut Widura.
Widura menatapku tajam. Ia sepertinya tidak menyukai pertanyaanku tadi.
“Kamu jangan mudah percaya omongan orang. Tidak ada yang perlu ditakutkan disini,” ucap Widura tegas.
“Mengapa kamu tidak takut?” tanyaku lagi.
Widura tampak enggan menjawab. Sorot matanya menunjukkan kelelahan.
“Orang-orang sekarang mudah percaya berita yang belum terbukti kebenarannya. Kadang kujumpai rakyat begitu mudah terhasut berita yang disebarkan oleh para patih Kerajaan Jambangan Sari,” ucap Widura.
Aku tidak segera paham yang diucapkan Widura. Kulirik pria berbadan tegap ini tampak mengepalkan tangan kanan dan memukulkan ke telapak tangan kiri. Ia kelihatan kesal. Sebagai Mahapatih Kerajaan Jambangan Sari, aku sudah terbiasa menghadapi tingkah laku pejabat penjilat dan bermuka dua. Tidak sulit bagiku untuk mengendalikan emosi diriku sendiri.
“Kami rakyat Sewu Klopo adalah korban persekongkolan para petinggi Kerajaan Jambangan Sari. Para patih kerajaan berlomba-lomba ingin mendapat pujian raja lantas mengabaikan nasib rakyat kecil,” Widura berkata dengan nada berapi-api.
“Apakah maksudmu para patih menindas penduduk kampung Sewu Klopo?” kataku dengan suara pelan. Aku masih ingin menggali informasi dari Widura tapi aku tidak mau pria di hadapanku ini sampai marah, kalap dan menerjangku.
“Bukan hanya sekali. Berkali-kali kami menjadi korban bagi tindakan sewenang-wenang pejabat istana. Aku adalah salah satu korban itu,” ucap Widura dengan suara bergetar dan hampir tidak terdengar.
“Kedua orang tuaku bahkan meninggal akibat difitnah oleh Mahapatih Kerajaan Jambangan Sari,” perkataan Widura mengagetkanku.
Tindakanku yang manakah yang telah menindas rakyat kecil. Seingatku, aku tidak pernah menganiaya penduduk desa.
“Aku turut bersedih atas hal itu. Bisakah kau ceritakan bagaimana awal mula orang tuamu ditindas?” ujarnya pelan.
Widura menghela nafas berat. Ia berdiri dan menatap lurus ke arah dinding bambu di sampingnya.
“Orangtuaku dihukum gantung karena didakwa membunuh seorang prajurit pemungut pajak. Mereka bahkan tidak pernah diadili terlebih dulu dan tahu-tahu dipancung di tiang gantungan,” kata Widura. Kulihat matanya berkaca-kaca.
Aku teringat kejadian beberapa tahun lalu saat aku memerintahkan algojo menghukum gantung sepasang suami-istri yang telah membunuh petugas pemungut pajak. Dalam aturan Kerajaan Jambangan Sari, hukuman untuk pelaku pembunuhan terhadap pejabat kerajaan sama beratnya dengan memberontak.
Saat itu aku telah mengumpulkan tiga orang saksi prajurit kerajaan yang mengiringi penarikan pajak. Dua orang diantaranya memberikan keterangan yang sama padaku bahwa suami-istri itu menolak membayar pajak meski memiliki banyak harta.
Seorang petugas pemungut pajak ditemukan tewas terbunuh saat bertugas. Sepasang suami-isteri itu pun mengakui perbuatannya telah membunuh petugas pajak. Apakah ada yang salah dalam pelaksanaan hukuman itu? Aku bertanya dalam hati.
“Widura, begitu banyak pejabat kerajaan Jambangan Sari berkuasa. Kupikir tidak semuanya berperilaku kejam seperti itu,” kataku pelan.
“Sama saja!” sahut Widura cepat.
Aku terkejut. Tidak kusangka Widura akan menuangkan amarahnya dengan berteriak seperti itu di hadapanku.
“Bagiku sama saja mereka semua. Mereka bersekongkol menindas rakyat. Maka jangan heran bila sekarang rakyat Sewu Klopo melawan,” Widura berkata demikian seraya mendekatkan wajahnya padaku.
Dia semakin dekat. Dan dekat. Tubuhku kaku. Aku bersiap mengepalkan tangan barangkali dia akan menyerangku tiba-tiba. Apakah dia sudah mengetahui penyamaranku? Apakah dia ingin mengancamku?
“Respati, jaga dirimu dan keluargamu baik-baik. Jangan sampai engkau menjadi korban kejahatan Sang Mahapatih,” ucapnya pelan seraya menepuk pundak kiriku.
Ah, untunglah.
“Terima kasih sudah mengingatkanku, Widura. Akan akan lebih hati-hati,” kataku sambil melempar senyum palsu.
“Kurasa sudah waktunya kita makan siang. Bagaimana kalau siang ini kita makan bersama?” ku ajak Widura makan untuk mengendurkan emosinya.
“Terima kasih, Respati. Aku belum lapar,” jawab Widura sekenanya.
Widura berpamitan padaku dan berjalan menuju salah satu kamar penginapan. Aku diam sebentar menunggu bayangannya hilang ditelan sudut penginapan. Setelah itu aku buru-buru mengikutinya. Aku melangkah sepelan mungkin sambil terus membuntutinya.
Widura menoleh ke kanan dan ke kiri sebelum memasuki sebuah kamar berhias bunga mawar di gagang pintunya. Kamar siapakah ini? Mengapa ia tampak tidak tenang? Apakah ada hal penting yang disembunyikannya?
Aku berjalan pelan. Kupilih lorong kecil diantara kamar itu dan kamar disampingnya untuk mengintai pergerakan Widura disana. Lorong itu hanya muat tubuh seorang manusia dan berbentuk memanjang ke belakang. Kuselipkan tubuhku disana. Kudekatkan telingaku ke dinding bambu.
“Kakang Widura sudah sampai?” terdengar suara wanita dari dalam kamar. Tunggu. Suara itu sepertinya milik Nyai Seroja, wanita pemilik penginapan yang kemarin menyambut kedatanganku disini.
“Ya, Nyai. Kakang baru saja menaikkan karung-karung ke kereta kuda di belakang,” giliran terdengar suara Widura.
“Bagaimana kabar Nyai? Apakah demam yang menyerangmu sudah hilang?” kata Widura penuh kekhawatiran.
“Nyai merasa lebih sehat. Kakang adalah obat terbaik untuk kesembuhanku. Melihat kedatangan Kakang Widura membuatku ingin cepat-cepat bergabung dengan kakang disana,” kata Nyai Seroja.
“Bersabarlah, Nyai. Kita masih akan terus berbagi tugas sampai keadaan memungkinkan kita untuk melakukan penyerangan,” kata Widura pelan.
Penyerangan apa yang dimaksud oleh Widura? Aku semakin penasaran dengan kelanjutan percakapan mereka.
“Kakang Widura persiapkan semua senjata dan melanjutkan pelatihan prajurit. Tujuan hidup nyai sekarang adalah Kakang Widura. Nyai akan selalu mendukung perjuangan Kakang Widura,” suara wanita itu masih terdengar pelan tapi tegas.
“Terima kasih, Nyai. Nyai adalah wanita paling hebat yang pernah kakang temui,” Ucap Widura.
Usai berkata demikian, tak terdengar lagi percakapan diantara dua manusia itu. Entah kegiatan apa yang mereka lakukan seterusnya di dalam. Aku masih menanti percakapan mereka. Tidak ada kata yang terucap. Hanya nafas berat yang samar terdengar saling bersahut-sahutan di dalam kamar.

Bagiku tak penting mengetahui kelanjutan aktifitas mereka. Aku segera berjingkat pelan ke arah kamar tidurku. Ku langkahkah kaki sepelan mungkin hingga tidak tersisa telapak kakiku.
Hari ini aku mendapatkan banyak informasi disini. Aku semakin yakin penginapan ini bukanlah rumah biasa. Pasti tempat ini berhubungan dengan markas para pemberontak Sewu Klopo.
Sekembali ke kamar tidurku, kurebahkan badan ke ranjang. Pikiranku mulai tertata. Aku masih belum percaya bahwa beberapa tahun silam aku telah menghilangkan nyawa sepasang suami-isteri di bawah tiang pancung. Kedua orang tua Widura telah mati akibat hukuman gantung yang kuperintahkan. Ya, aku masih ingat kejadian beberapa tahun lalu itu.
Saat itu aku memerintahkan tiga orang prajurit untuk mengumpulkan pajak dari rumah-rumah penduduk Sewu Klopo. Pajak itu setara dengan biaya keamanan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Jambangan Sari untuk membayar para prajurit di tapal batas. Kupikir impas bila kerajaan menarik pajak untuk menjamin ketenteraman hidup rakyatnya.
Sayangnya, dari tiga orang petugas penarik pajak itu yang kembali dalam keadaan hidup hanya tersisa dua orang. Seorang petugas dilaporkan tewas dibunuh oleh sepasang suami-isteri penduduk Sewu Klopo. Aku kalap mendengar laporan dua prajurit itu. Segera kuperintahkan sepuluh orang prajurit kerajaan untuk membawa paksa suami-isteri pembunuh ke istana.
Sepasang suami-isteri itu telah dihadirkan oleh prajurit di aula Kerajaan Jambangan Sari. Tidak ada pejabat lain disana waktu itu. Hanya ada aku dan beberapa orang prajurit pilihan.
“Benarkah kalian yang membunuh petugas penarik pajak?” kataku tegas.
“Benar. Kami yang membunuhnya,” ucap si suami pelan. Tidak sedikitpun ia memancarkan rasa takut. Besar juga nyalimu, gumamku.
“Mengapa kalian membunuhnya?” sergahku tak sabar.
“Kami tidak sengaja,” pria pembunuh itu berdalih.
“Mana ada membunuh karena tidak sengaja,” ujar salah satu prajurit yang menjadi saksi kejadian. “Kalian hanya mencari alasan supaya tidak dihukum,” tambahnya.
Sepasang suami isteri ini terus berdalih tidak memiliki niat membunuh petugas pajak. Kupikir tidak ada gunanya bagiku berbicara panjang lebar dengan mereka. Kuperintahkan para prajurit menyeret mereka berdua ke tiang gantungan.
Menghukum mereka secepat mungkin itu lebih baik. Aku tidak ingin dibuat malu di hadapan raja. Terlebih lagi di hadapan para patih kerajaan yang terkenal culas dan suka mencari perhatian raja.
Algojo tiba dan telah memasang sepasang tali gantungan. Tampak pria tua itu ingin berkata sesuatu. Aku memberikan kesempatan baginya untuk berkata untuk terakhir kalinya.
“Katakan apa pesan terakhirmu,” sergahku tidak sabar.
Pria itu tidak segera berkata. Dia memandangku dan dua orang algojo disampingnya.
“Kelak Mahapatih akan menyesali keputusan ini. Biarkan hamba dan isteri hamba menjadi korban terakhir ketidakadilan Mahapatih. Ingatlah satu saat nanti akan tiba. Ketika api tersulut di utara perkampungan Sewu Klopo, saat itulah tanda akhir hidup Anda,” ujar pria itu penuh keyakinan.
Aku mendengar dengan mata terbelalak. Setengah buluh kudukku merinding ketakutan mendengar ancamannya. Inginku menurunkan pria itu dari tiang gantungan. Tapi apa kata pejabat istana bila sampai itu terjadi. Aku akan dicap sebagai pejabat pengecut yang plin-plan dan takut ancaman rakyat jelata.
Ku angkat tangan kananku. Algojo paham. Segera tali pancung dikaitkan di leher pria itu. Hanya perlu beberapa waktu saja untuk melepaskan nyawa dari tubuhnya. Tubuh pria itu mengejang beberapa saat hingga melemas di bawah tali hukuman.
Wanita di sampingnya menangis histeris. Ia ingin meraih jasad suaminya tapi tidak mampu. Ikatan tali di tangannya sangat kuat. Tenaganya tidak cukup untuk melepas ikatan itu. Tangisnya tidak berhenti sampai tubuh tanpa nyawa itu ditarik paksa oleh algojo ke belakang gudang. Disana telah digali dua lubang besar seukuran tubuh manusia dewasa.
Dalam tangisnya, wanita itu berkata dengan mata melotot tertuju padaku, “Aku bersumpah tidak akan membiarkan kebahagiaan hadir di hidupmu. Meskipun engkau seorang Mahapatih yang bergelimang harta, engkau tidak akan pernah menemukan wanita yang sanggup menjadi isterimu. Ingatlah kata-kata seorang janda yang sebentar lagi akan menjadi mayat ini.”
Sekali lagi aku terperanjat oleh ucapan pesakitan di hadapanku. Lagi-lagi aku harus mengangkat tanganku ke arah algojo. Senasib dengan suaminya, wanita ini harus mati di bawah tiang gantungan. Tubuhku bergetar saat menyadari hari itu aku telah menghilangkan nyawa dua orang rakyat yang seharusnya kulindungi.
Tidak ada pejabat tinggi istana yang tahu kejadian ini. Dua orang petugas penarik pajak dan para algojo kututup mulutnya rapat-rapat agar tidak bercerita kepada siapapun. Masing-masing dari mereka telah menerima sekantong uang dariku. Itu cukup untuk membuat mereka diam.
Yang tersisa detik ini adalah aku merasakan sesak di dada. Perlahan aku mendesah. Apakah kutukan suami-isteri itu akan benar terjadi padaku?
Saat kesadaranku telah pulih, aku baru tahu hari telah menjelang sore. Aku bergegas mencari makanan pengisi perut. Kali ini aku tidak ingin makan di penginapan. Aku ingin menyelidiki bagian utara wilayah Sewu Klopo. Aku berjalan keluar kamar menuju kandang kuda. Bersyukur Waskita telah memberi makan kudaku sekaligus memandikan tadi pagi. Kuda itu kini tampak bugar.
Baru saja kuda kupacu menuju pelataran penginapan. Langkah kuda terhenti oleh kereta Widura yang akan keluar menuju jalan desa. Keberadaan kereta menghalangi langkah kudaku. Tapi tunggu dulu, bukankah tadi hanya ada lima karung bahan makanan yang dipesan. Mengapa sekarang ada enam karung di dalam kereta? Sebuah karung lagi berisi benda apakah itu?
(bersambung)
Baca cerita selanjutnya: Hitam Putih Sang Mahapatih (Bagian 4)
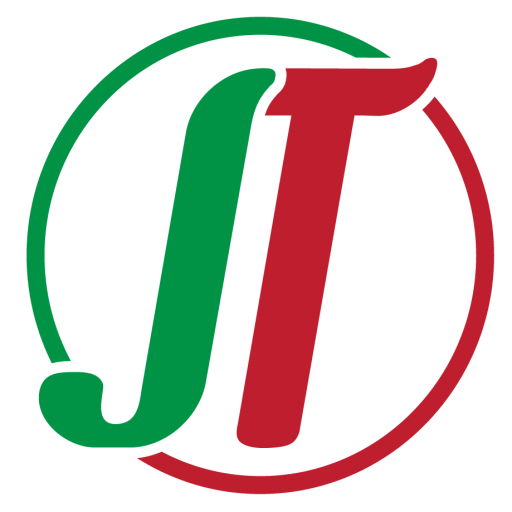
Tinggalkan Balasan