
“Ini sudah hari terakhir. Apakah kamu yakin hari ini kita akan berhasil, suamiku?” tanya Aryanti pada Adinata. Pria yang telah menjadi suaminya selama dua puluh delapan tahun itu tersenyum. Kedua tangannya menggenggam erat jemari isterinya.
“Kita lihat saja nanti,” jawab Adinata singkat.
Segera suami-isteri ini bergegas ke tempat yang telah disepakati. Mereka menyusuri pinggiran sungai. Jalan setapak selebar dua langkah orang dewasa itu mereka jejaki. Aliran air sungai hampir tidak terdengar. Pendalaman sungai terjadi selama beberapa tahun terakhir akibat penambangan pasir secara liar. Tidak ada lagi gemercik suara air yang menenangkan. Suram, sepertihati keduanya. Kilatan bayangan jarum suntik dan bau obat-obat kimia masih tersisa dalam pikiran mereka.
Untungnya masih tersisa sekawanan burung emprit yang berkejaran di tanah. Sesekali hewan mungil ini bertingkah laku lucu sehingga kerap kali menggoda siapa saja warga desa untuk memandangnya lebih lama. Namun hal itu tidak berlaku untuk Adinata dan Aryanti. Hari ini mereka harus tiba di sisi lain desa ini lebih cepat. Sore hari nanti mereka akan sangat sibuk membuat tumpeng dan mengabari kerabat.
Ratusan tonggak kayu tertancam di tanah lapang. Satu diantara sepasang kayu itu tertulis nama-nama warga desa yang telah mereka kenal sebelumnya. Bukan hanya dikenal, tetapi juga mereka jaga keberadaannya saat anggota keluarganya telah mulai lupa. Taburan kelopak bunga tampak mengering pada beberapa gunduk tanah disana.
“Ayo kita tunggu disana,” ujar Adinata seraya menunjuk sebuah gubuk kecil di tengah tanah lapang. Terdapat sebuah pohon mangga berdahan lebat di belakang gubuk. Semilir udara siang hari mengelus pipi Aryanti di musim kemarau yang jarang turun hujan ini.
“Mungkin sikap kita sudah keterlaluan pada Abimana. Tidak seharusnya kita berperilaku seperti ini,” ucap Aryanti dengan cemas.
“Sudah kubilang kamu diam saja. Lihatlah sebentar lagi siapa yang akan datang kesini,” jawab Adinata dengan tegas. Ia seolah tidak terpengaruh kekhawatiran isterinya.
Sudah menjelang tengah hari. Tidak ada orang lain yang datang menemui mereka berdua. Aryanti hampir putus asa. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak mampu membayangkan perpisahan yang segera dialami sebentar lagi.
“Sepertinya kita belum beruntung kali ini,” Aryanti mendengus pelan dan hampir tidak terdengar oleh pria yang duduk disampingnya.
Srek.. Srek… Sreeeek…
Pendengaran suami-isteri itu menangkap adanya langkah kaki yang semakin dekat di belakang mereka. Tanpa diperintah, mereka menoleh ke belakang. Tampak seorang gadis berjalan pelan dengan pandangan mata tertunduk. Kerudung putih yang dipakainya berkibar dalam hembusan angin muson timur.
“Paman… Bibi… Saya datang,” kata gadis itu saat tiba di hadapan Adinata dan Aryanti.
“Duduklah disini, Kirana.” ucap Aryanti dengan ramah. Binar matanya tidak bisa disembunyikan lagi. Dia menggandeng tangan gadis yang dipanggilnya Kirana. Dipandangnya gadis itu dengan lekat.
“Apakah kamu sudah bulat hati untuk datang kesini?” tanya Adinata tegas.
“Ya, paman. Saya sadar dan tidak dipaksa siapapun,” kata Kirana.
“Terima kasih, nak Kirana. Bibi senang akhirnya kamu bersedia,” ucap Aryanti sambil menghamburkan diri memeluk tubuh gadis mungil ini.
Tiga hari yang lalu pasangan suami-isteri Adinata dan Aryanti telah mengumumkan sayembara yang menggemparkan seluruh warga desa. Mereka sedang mencari seorang menantu yang akan dinikahkan dengan putra semata wayangnya, Abimana. Syarat menjadi menantunya tidak sulit tapi cukup aneh, harus bersedia datang di tempat pemakaman umum pada tengah hari.
“Tidak perlu heran. Kalian semua kelak juga akan berkumpul di makam ini,” demikian perkataan Adinata setiap kali warga desa menanyakan mengapa harus bertemu disana.
Suami-isteri itu menambahkan lagi bahwa pernikahan itu hanya akan berlangsung selama empat belas hari. Setelah lewat dari masa tersebut, wanita itu akan dipisahkan dengan anaknya yang kini tergolek lemah di bawah perawatan dokter dan suster. Tenaga medis telah memvonis Abimana mengidap penyakit menular dan umurnya tidak akan lama.
Sudah dua hari berturut-turut Adinata dan Aryanti menelan kekecewaan bahwa tidak satupun wanita lajang yang bersedia mengikuti sayembara ini. Hingga kini hadir seorang Kirana yang tak lain adalah murid Abimana di madrasah aliyah tempatnya mengajar.
“Mengapa nak Kirana mau menikah dengan Abimana walau dia sedang mengidap penyakit menular?” tanya Adinata.
“Sehat dan sakit bukanlah alasan bagi saya untuk meniadakan rasa sayang di hati saya. Mas Abimana adalah jawaban atas doa-doa saya di setiap penghujung malam,” kata Kirana dengan pandangan mata tetap terarah ke tanah.
“Bukanlah pernikahan ini hanya akan berlangsung selama empat belas hari? Setelah itu mungkin kamu akan menjadi janda yang ditinggal mati suaminya. Apa kata orang-orang nanti jika diumurmu yang masih muda ini kamu telah menjadi janda,” tanya Aryanti.
Kirana mengangkat wajahnya. Senyum terkembang di wajah cantiknya. Dia meraih kedua pasang tangan suami-isteri di hadapnya.
“Perlu paman dan bibi ketahui. Menikah sehari, empat belas hari, ataupun empat belas tahun bukanlah jaminan bagi kita untuk bisa hidup bahagia. Saya jatuh cinta kepada Mas Abimana sejak pertama kali bertemu. Saya ingin menyempurnakan separuh amal ibadah Mas Abimana sebelum nafas terakhirnya. Jika kelak saya benar-benar menjadi janda, maka saya rela menderita penyakit yang sama dan dikuburkan di liang yang sama,” kata Kirana.
Aryanti tak bisa menahan emosi. Air matanya bercucuran membasahi pipinya. Adinata hanya mampu terdiam mendengar pengakuan tulus Kirana. Mereka bertiga berpelukan di gubuk yang menjadi tempat bekerja Adinata sehari-hari sebagai juru kunci makam.
SELESAI.
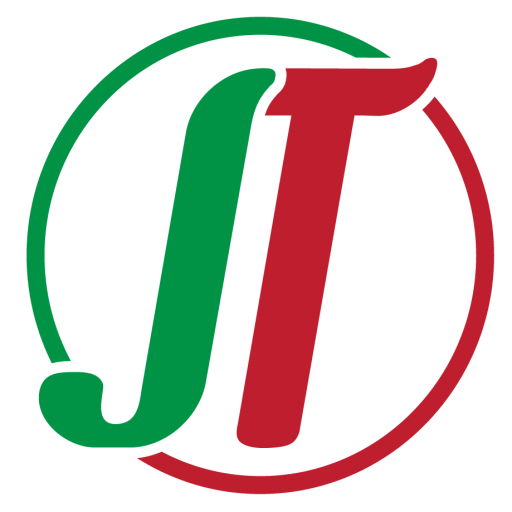
Tinggalkan Balasan